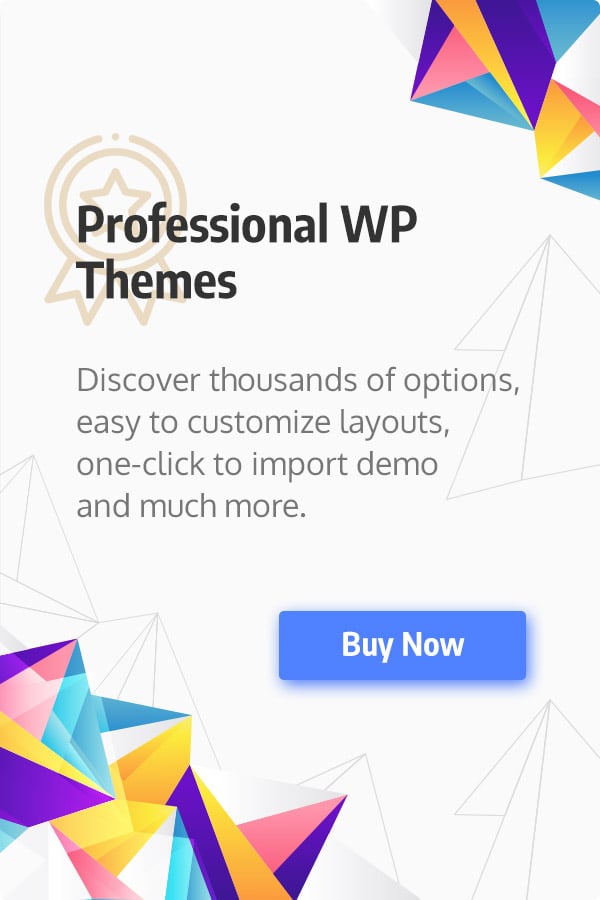Lahir dan mati itu memang siklus alamiah, valid. Tapi kalau yang “pamit” adalah seorang Public Figure, apalagi levelnya Founding Father, ceritanya jadi nggak sederhana. Kita sebagai netizen—atau rakyat—punya hak buat tahu: Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
Bayangkan, jika kamu adalah orang paling berpengaruh di Asia-Afrika. Orator jenius yang bikin dunia gemetar cuma lewat pidato. Tapi di akhir hidupmu, kamu mati kesepian, terkurung di kamar yang suram, dijaga tentara, dan bahkan susah minta obat sakit gigi.
Inilah kisah hari-hari terakhir Bung Karno. Bukan sebagai Presiden yang gagah di mimbar, tapi sebagai manusia biasa yang “dihancurkan” pelan-pelan.
Dipaksa “Log Out” dan Di-Banned dari Kehidupan Nyata
Setelah prahara politik 1965-1967, Bung Karno nggak cuma kehilangan jabatan. Dia kena cancel culture paling brutal dalam sejarah Indonesia. Dari Istana yang megah, dia dipindahkan ke Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala).
Statusnya? Tahanan rumah. Vibes-nya di sana bukan istirahat pensiun, tapi isolasi total. Bayangkan social distancing saat pandemi kemarin, tapi ini dipaksakan, dijaga senapan, dan kamu nggak boleh pegang HP atau koran sama sekali.
Perang Psikologis: “Membunuh” Tanpa Menyentuh
Buat Gen Z yang aware banget soal mental health, apa yang dialami Bung Karno itu definisi toxic treatment level dewa.
Rezim Orde Baru tahu, membunuh Bung Karno secara fisik bakal bikin rusuh satu negara. Jadi, strateginya diganti: Hancurkan mentalnya.
Akses “Diblokir”: Koran, radio, TV? Big No. Bung Karno nggak boleh tahu dunia luar.
Support System Dihapus: Ajudan setia dan dokter pribadinya diusir. Diganti sama orang-orang baru yang “dingin” dan kaku.
Family Time Dibatasi: Anak-anaknya (termasuk Bu Megawati dan Bu Rachmawati yang saat itu masih muda) kalau mau jenguk Bapak harus lewat prosedur izin militer yang ribetnya minta ampun. Pas ketemu pun, diawasi ketat. Nggak ada deep talk leluasa.
Si Singa Podium itu dipaksa diam seribu bahasa. Kesepian inilah yang bikin penyakit ginjalnya makin parah karena stres berat (psikosomatis).
Misteri Medis: Penelantaran atau Kesengajaan?
Ini bagian paling dark. Banyak kesaksian—termasuk dari Rachmawati—yang nge-spill kalau fasilitas kesehatan buat Bung Karno itu nggak layak.
Bayangkan, seorang mantan Presiden RI, kamarnya jorok dan bau. Obat-obatannya seringkali nggak jelas. Ada desas-desus kalau alat medis canggih sengaja ditarik. Bung Karno dibiarkan “melawan” penyakit komplikasi sendirian dengan fasilitas minim.
Gigi sakit? Dibiarkan.
Ginjal bengkak? Obat seadanya.
Ini bukan lagi soal politik, ini soal kemanusiaan yang dicabut paksa. Seolah-olah skenarionya adalah: “Biarkan sakitnya yang bekerja mengakhiri hidupnya.”
The Sad Ending
16 Juni 1970, tubuh sang Proklamator akhirnya menyerah. Dia koma dan dilarikan ke RSPAD. Lima hari kemudian, 21 Juni 1970, Bung Karno wafat.
Bahkan sampai meninggal pun, dia nggak punya kuasa atas dirinya sendiri. Wasiatnya minta dimakamkan sederhana di bawah pohon rindang di Priangan (Bogor), supaya adem. Tapi, penguasa saat itu menolak. Jenazahnya diterbangkan ke Blitar, Jawa Timur. Alasannya “penghormatan”, tapi banyak yang baca itu sebagai strategi politik biar makamnya jauh dari Jakarta (pusat kekuasaan).
Refleksi Kita Hari Ini
Kisah ini ngasih pelajaran mahal: Bahwa politik bisa sangat kejam, bahkan pada orang yang memberikannya panggung. Bung Karno yang memerdekakan bangsa ini, justru meninggal dalam kondisi tidak merdeka.
So, next time kamu lihat foto Bung Karno yang gagah pakai peci dan kacamata hitam, ingat juga sisi rapuhnya di Wisma Yaso. Sisi manusiawi yang mengajarkan kita bahwa pahlawan juga bisa patah hati, kesepian, dan kalah.